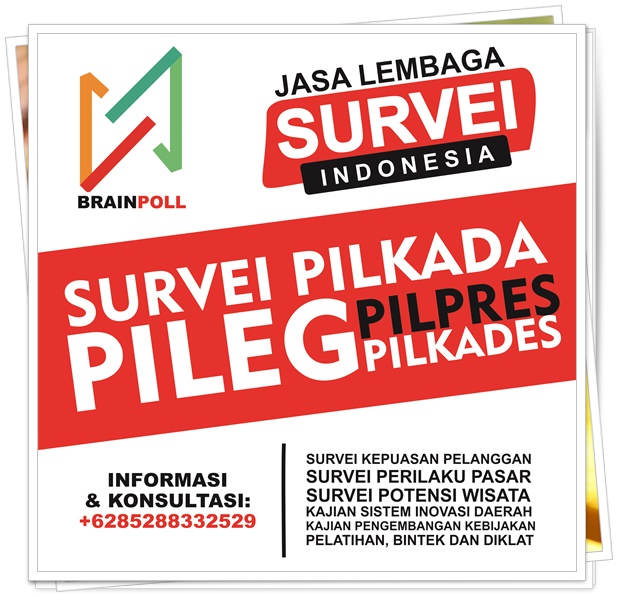Putusan Pengadilan Lawan Konstitusi, Syarifah Korban Pasal Mati
Redaksi - Selasa, 8 Juli 2025 | 21:30 WIB
Post View : 18

Di negeri hukum, seorang warga masih bisa dipenjara atas dasar pasal yang sudah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Itulah ironi yang tengah dialami Syarifah Hayana, Ketua DPD-LPRI Kalimantan Selatan.
Banuaterkini.com, BANJARMASIN - Syarifah Hayana tetap divonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin, kendati dasar hukum yang digunakan untuk menjebloskannya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XXIII/2025.
Putusan PT Banjarmasin No. 135/PID.SUS/2025/PT BJM yang dibacakan pada Jumat, 4 Juli 2025, menjadi sorotan tajam banyak kalangan.
Bukan hanya karena menguatkan vonis terhadap Syarifah, tetapi juga karena dilakukan sehari sebelum bukti hukum baru, putusan Mahkamah Konstitusi, didaftarkan secara resmi oleh tim kuasa hukumnya.
“Ini bukan sekadar salah tafsir. Ini pelecehan terhadap konstitusi,” ujar Kisworo Dwi Cahyono, salah satu aktivis hukum yang ikut mendampingi Syarifah.
Pasal Mati yang Menghidupkan Vonis
Pasal 128 huruf k dalam Undang-Undang Pilkada menjadi alat utama menjerat Syarifah, hanya karena organisasinya menghitung Formulir C1 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru.
Aktivitas itu diklaim sebagai “quick count ilegal” oleh pihak yang tak bertanggung jawab, meskipun LPRI tercatat sebagai pemantau pemilu resmi.
Padahal, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pasal tersebut bersifat karet, multitafsir, dan berbahaya bagi kebebasan sipil.
Dalam putusannya, MK menegaskan norma itu bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
Namun, PT Banjarmasin tetap menutup mata. Pertimbangan terhadap putusan MK tidak disinggung dalam amar putusan.
“Padahal dalam negara hukum, konstitusi adalah sumber utama. Jika putusan MK diabaikan, maka kita mundur ke zaman di mana hukum hanya alat kekuasaan,” kata Ketua Tim Hukum Haram Manyarah (Hanyar), Dr Muhamad Pazri, kuasa hukum Syarifah, dalam keterangannya, Selasa (08/07/2025).
Bukan Sekadar Syarifah, Tapi Wajah Demokrasi
Syarifah bukan hanya seorang pemantau pemilu. Ia adalah wajah dari masyarakat sipil yang aktif memastikan demokrasi berjalan jujur dan adil.
Kini ia menjadi simbol betapa mudahnya hukum dipakai untuk membungkam suara yang kritis.
Senior Tim Hukum Hanyar, Prof. Denny Indrayana menyebut kasus ini sebagai titik kritis bagi masa depan pengawasan pemilu di Indonesia.
“Bayangkan jika setiap pemantau bisa dikriminalisasi hanya karena menjalankan tugasnya. Ini akan membunuh partisipasi rakyat dalam demokrasi,” ujarnya.
Saat Hukum Kehilangan Nurani
Kasus Syarifah menjadi refleksi suram wajah peradilan di Indonesia, ketika hakim tinggi mengabaikan norma tertinggi dalam sistem hukum.
Dalam perspektif hukum pidana, asas nullum delictum nulla poena sine lege, tidak ada kejahatan tanpa hukum, harusnya menjadi dasar utama pembatalan vonis tersebut.
Pasal 1 ayat (2) KUHP juga mewajibkan penerapan hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Namun dalam praktik, asas ini seakan tak lebih dari teks kosong di tengah ruang sidang yang dingin.
“Ini bukan soal hukum semata. Ini soal nurani. Ketika hakim tak lagi mendengar jeritan keadilan, maka hukum berubah menjadi senjata yang membunuh kepercayaan rakyat,” kata Pazri.
Langkah Terakhir, Peninjauan Kembali
Kini, Tim Hukum Hanyar tengah menyiapkan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Sebuah jalan panjang yang tak mudah, namun menjadi satu-satunya harapan mengembalikan hak konstitusional Syarifah dan marwah peradilan itu sendiri.
“Kami tidak hanya membela satu orang. Kami membela prinsip. Kalau kita diam hari ini, maka besok siapa pun bisa jadi korban pasal mati,” pungkas Pazri.
Tags
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Terkini
Polda Kalsel Perkuat Program Ketahanan Pangan di Daerah
Kamis, 6 November 2025 | 18:53 WIB
Bupati dan Kapolres Bogor Kompak Hadapi Potensi Bencana Alam
Kamis, 6 November 2025 | 13:14 WIB
PKB Siapkan Langkah Internal, Nasib Gubernur Riau Ditentukan
Kamis, 6 November 2025 | 13:07 WIB
Polda Kalsel Perkuat Program Ketahanan Pangan di Daerah
Kamis, 6 November 2025 | 18:53 WIB
Bupati dan Kapolres Bogor Kompak Hadapi Potensi Bencana Alam
Kamis, 6 November 2025 | 13:14 WIB
PKB Siapkan Langkah Internal, Nasib Gubernur Riau Ditentukan
Kamis, 6 November 2025 | 13:07 WIB



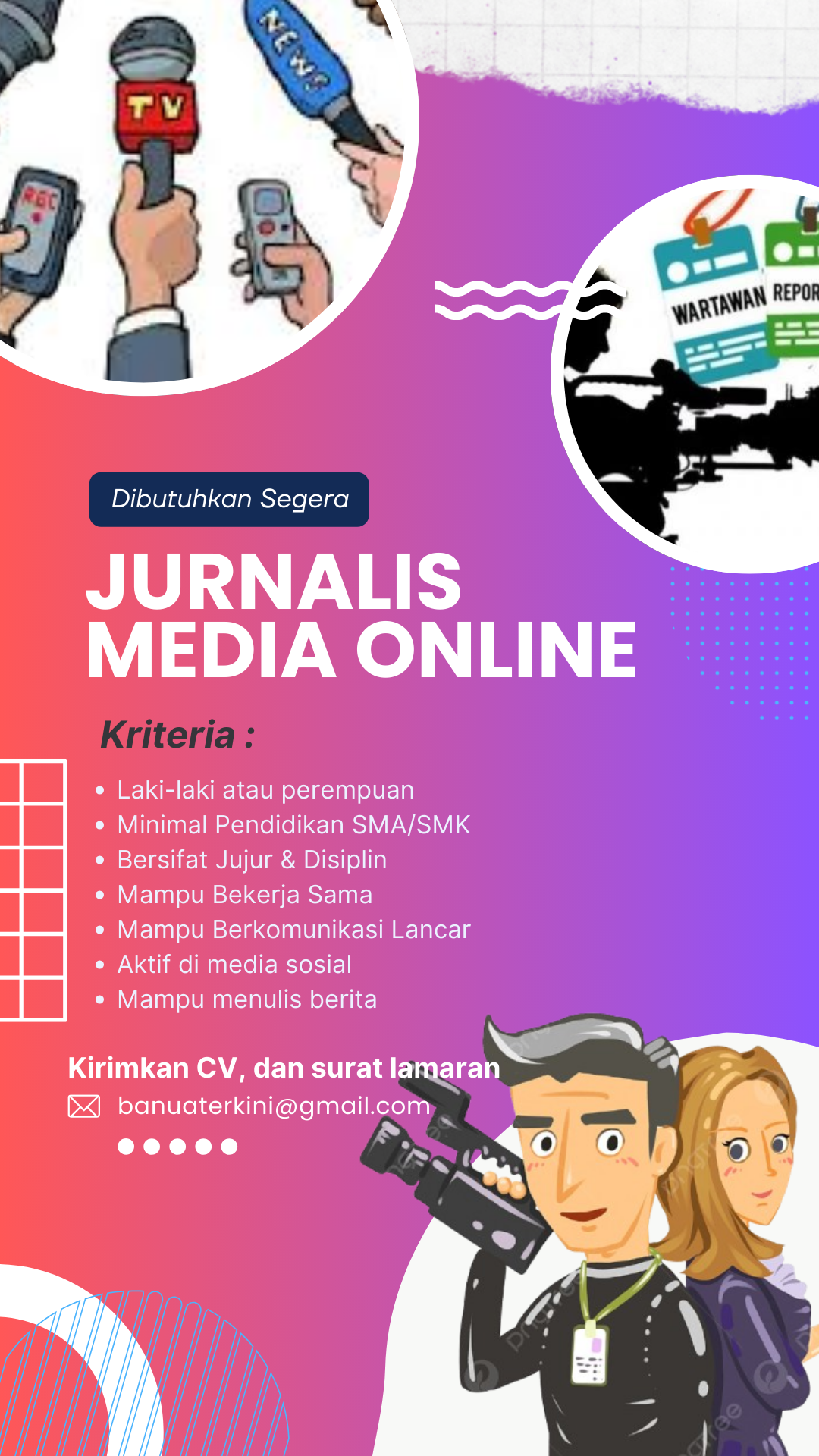
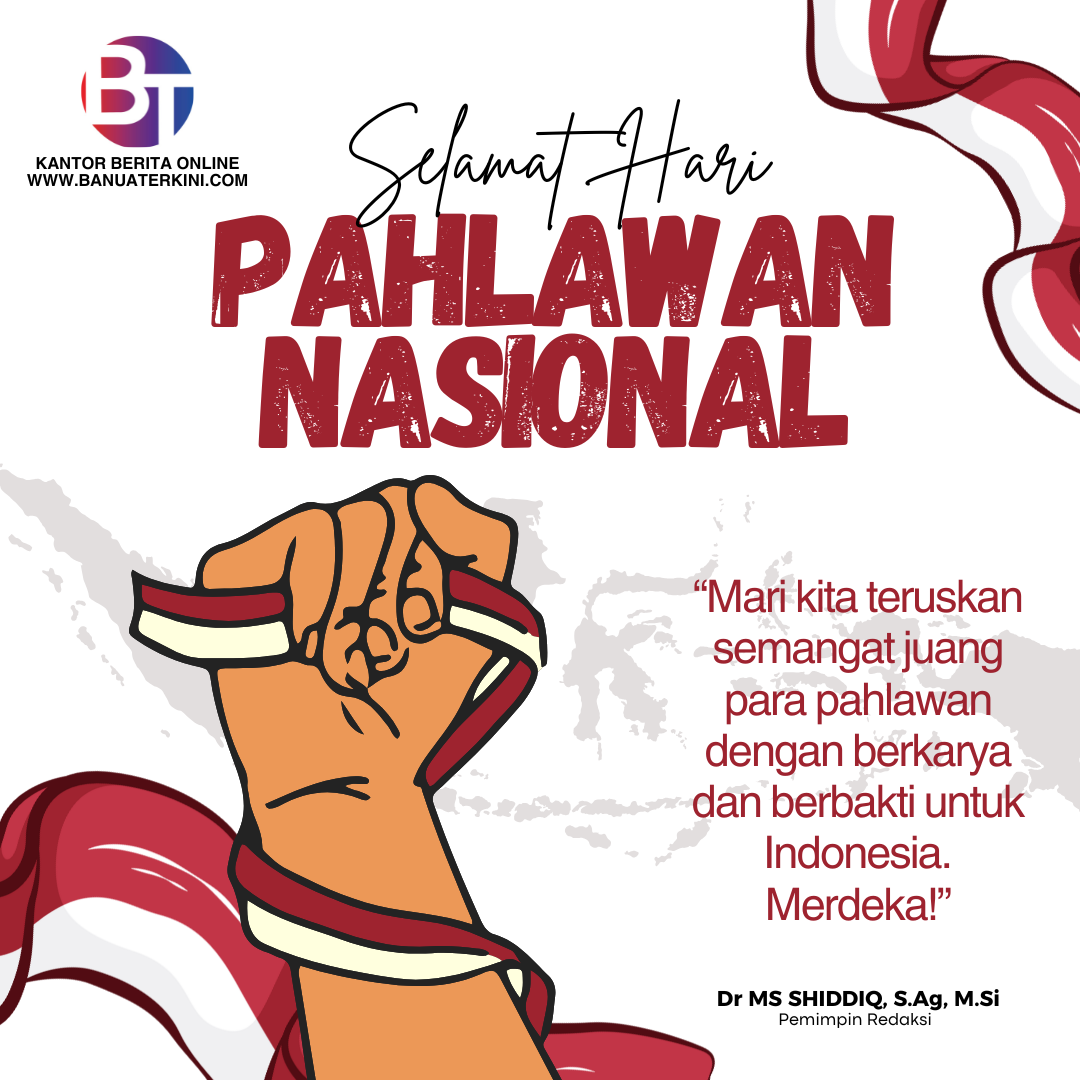
Terpopuler



Terpopuler