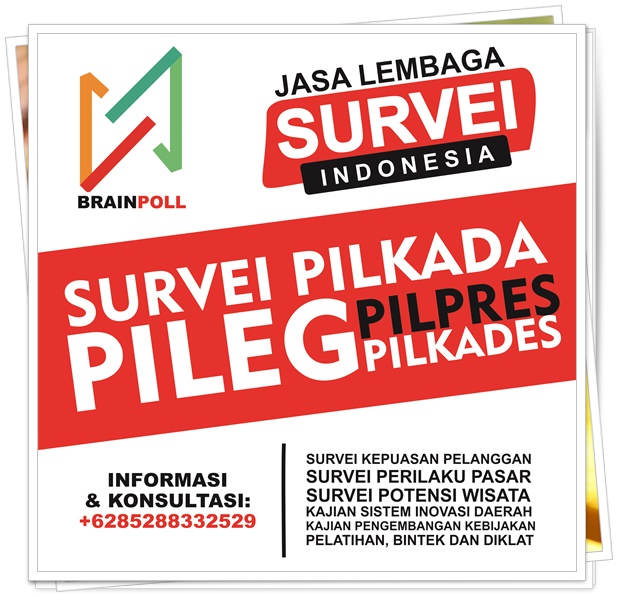27 Tahun Reformasi, Harapan atau Delusi?
Redaksi - Rabu, 21 Mei 2025 | 11:51 WIB
Post View : 81

Dua puluh tujuh tahun lalu, jutaan rakyat turun ke jalan. Mereka menuntut perubahan, menggugat kekuasaan absolut, dan menyerukan lahirnya tatanan baru yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Reformasi 1998 bukan sekadar pergantian rezim, tetapi janji kolektif menuju bangsa yang beradab. Namun hari ini, di usia ke-27 reformasi, publik dipaksa kembali bertanya, benarkah perubahan itu masih berjalan, atau justru telah menjadi delusi yang dipelihara oleh elite?
 Oleh: Ahmad Gafuri *)
Oleh: Ahmad Gafuri *)
Reformasi lahir dari penderitaan rakyat yang tercekik krisis ekonomi dan dikhianati oleh sistem kekuasaan yang korup dan represif.
Tuntutan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), supremasi hukum, pemilu yang jujur dan adil, serta desentralisasi kekuasaan diwujudkan dalam berbagai kebijakan penting, mulai dari amandemen UUD 1945 hingga lahirnya UU Otonomi Daerah pada 1999.
Namun apa yang kita saksikan hari ini? Di berbagai daerah, otonomi justru melahirkan raja-raja kecil yang mempermainkan anggaran.
Korupsi tumbuh subur di ruang-ruang kekuasaan lokal. Pilkada yang digadang-gadang sebagai wujud demokrasi langsung berubah menjadi ajang transaksional yang mengabaikan integritas dan gagasan.
Kalimantan Selatan, yang semestinya menjadi contoh kemajuan tata kelola daerah, justru tidak luput dari praktik semacam ini.
Contoh mutakhir datang dari dinamika Pilkada Banjarbaru yang diwarnai kontroversi dugaan politik uang, ketidaknetralan ASN, hingga maraknya hoaks politik.
Alih-alih mencerdaskan rakyat, kontestasi lokal justru menyuburkan apatisme dan sinisme. Reformasi yang semestinya memuliakan rakyat, hari ini lebih banyak memfasilitasi kepentingan elite dan oligarki.
Fenomena ini memperlihatkan betapa reformasi belum sepenuhnya menembus dinding budaya politik kita.
Demokrasi yang diidealkan menjadi sarana keadilan sosial, justru terjebak dalam demokrasi prosedural yang kehilangan ruh.
Seperti yang dikemukakan Larry Diamond, demokrasi sejati tak hanya soal pemilu, tetapi tentang pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan bermoral.
Reformasi dalam Evaluasi Kritis
Laporan ICW dan KPK dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren korupsi yang konsisten tinggi di level daerah.
Aparat penegak hukum pun tak jarang terseret dalam konflik kepentingan. Di tengah situasi seperti ini, publik bertanya dengan getir, apakah reformasi telah membawa harapan, atau hanya menyisakan ilusi?
Lebih menyakitkan, sebagian elite politik justru dengan enteng mengatakan bahwa era reformasi telah selesai. Narasi semacam ini berbahaya.
Ia membungkam evaluasi kritis dan mengubur semangat korektif dalam demokrasi.
Jalan Masih Panjang
Reformasi bukan produk, melainkan proses. Ia bukan tujuan, tetapi jalan panjang yang mesti terus dijaga dan diperjuangkan.
Reformasi tidak boleh hanya dikenang sebagai peristiwa heroik masa lalu. Ia harus dievaluasi secara kritis dan disesuaikan dengan konteks zaman.
Terutama di daerah seperti Kalimantan Selatan, yang memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan.
Lalu, pertanyaannya hari ini adalah apakah reformasi masih membawa perbaikan atau justru kemunduran?”
Pertanyaan tersebut seharusnya tidak hanya menjadi renungan, tetapi juga menjadi kompas arah gerak bagi para pemimpin, birokrat, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menjaga agar cita-cita reformasi tidak dikhianati oleh sistem yang semakin permisif terhadap praktik koruptif.
Dalam usia 27 tahun ini, sudah waktunya kita bertanya dengan jujur, adakah kita masih di jalur perubahan, atau justru sedang tersesat dalam delusi kekuasaan?
Jawaban itu tidak bisa hanya diberikan oleh elite, tetapi oleh setiap warga negara yang masih percaya bahwa negeri ini layak diperbaiki.
*) Mantan Aktivis 1998, Sekretaris Umum HMI Cabang Banjarmasin 1996-1997
Tags
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Terkini
Santri Lirboyo dan Alumni Pesantren Serukan Boikot Trans7
Rabu, 15 Oktober 2025 | 21:12 WIB
UNUKASE Tekankan Karakter dan Komitmen Moral Penerima KIP Kuliah
Rabu, 15 Oktober 2025 | 18:16 WIB
Kejari Kawal Sinergi Bandarmasih dan PALD Kembalikan Dana Pelanggan
Rabu, 15 Oktober 2025 | 17:37 WIB
Propam Polda Kalsel Sidak Logistik Polri di Polres Tabalong
Rabu, 15 Oktober 2025 | 17:14 WIB
Praperadilan Ditolak, Penahanan Nadiem Makarim Dinyatakan Sah
Selasa, 14 Oktober 2025 | 20:40 WIB
Pemuda Daerah Siap Jadi Wakil Indonesia di Program PPAN 2025
Selasa, 14 Oktober 2025 | 20:39 WIB
Purbaya Pastikan Impor Pakan Ternak di Priok Sesuai Aturan
Selasa, 14 Oktober 2025 | 20:37 WIB
Dua Bos Perusahaan di Kalselteng Terbukti Gelapkan Pajak Miliaran
Selasa, 14 Oktober 2025 | 17:00 WIB
Warga Banjarmasin Terdampak Kebocoran Pipa PAM Bandarmasih
Selasa, 14 Oktober 2025 | 12:55 WIB
Santri Lirboyo dan Alumni Pesantren Serukan Boikot Trans7
Rabu, 15 Oktober 2025 | 21:12 WIB
UNUKASE Tekankan Karakter dan Komitmen Moral Penerima KIP Kuliah
Rabu, 15 Oktober 2025 | 18:16 WIB
Kejari Kawal Sinergi Bandarmasih dan PALD Kembalikan Dana Pelanggan
Rabu, 15 Oktober 2025 | 17:37 WIB
Propam Polda Kalsel Sidak Logistik Polri di Polres Tabalong
Rabu, 15 Oktober 2025 | 17:14 WIB
Praperadilan Ditolak, Penahanan Nadiem Makarim Dinyatakan Sah
Selasa, 14 Oktober 2025 | 20:40 WIB
Pemuda Daerah Siap Jadi Wakil Indonesia di Program PPAN 2025
Selasa, 14 Oktober 2025 | 20:39 WIB
Purbaya Pastikan Impor Pakan Ternak di Priok Sesuai Aturan
Selasa, 14 Oktober 2025 | 20:37 WIB
Dua Bos Perusahaan di Kalselteng Terbukti Gelapkan Pajak Miliaran
Selasa, 14 Oktober 2025 | 17:00 WIB
Warga Banjarmasin Terdampak Kebocoran Pipa PAM Bandarmasih
Selasa, 14 Oktober 2025 | 12:55 WIB



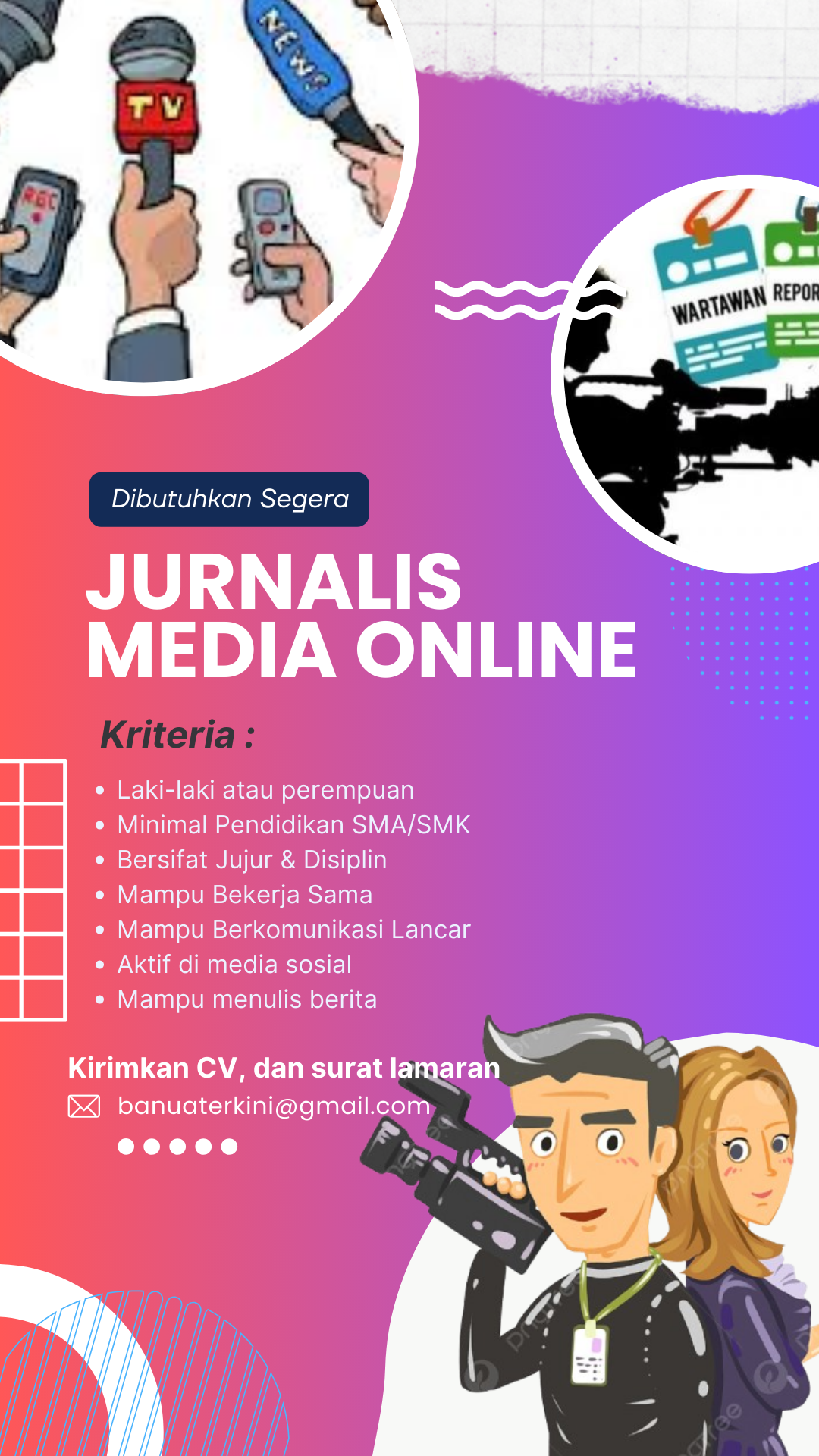
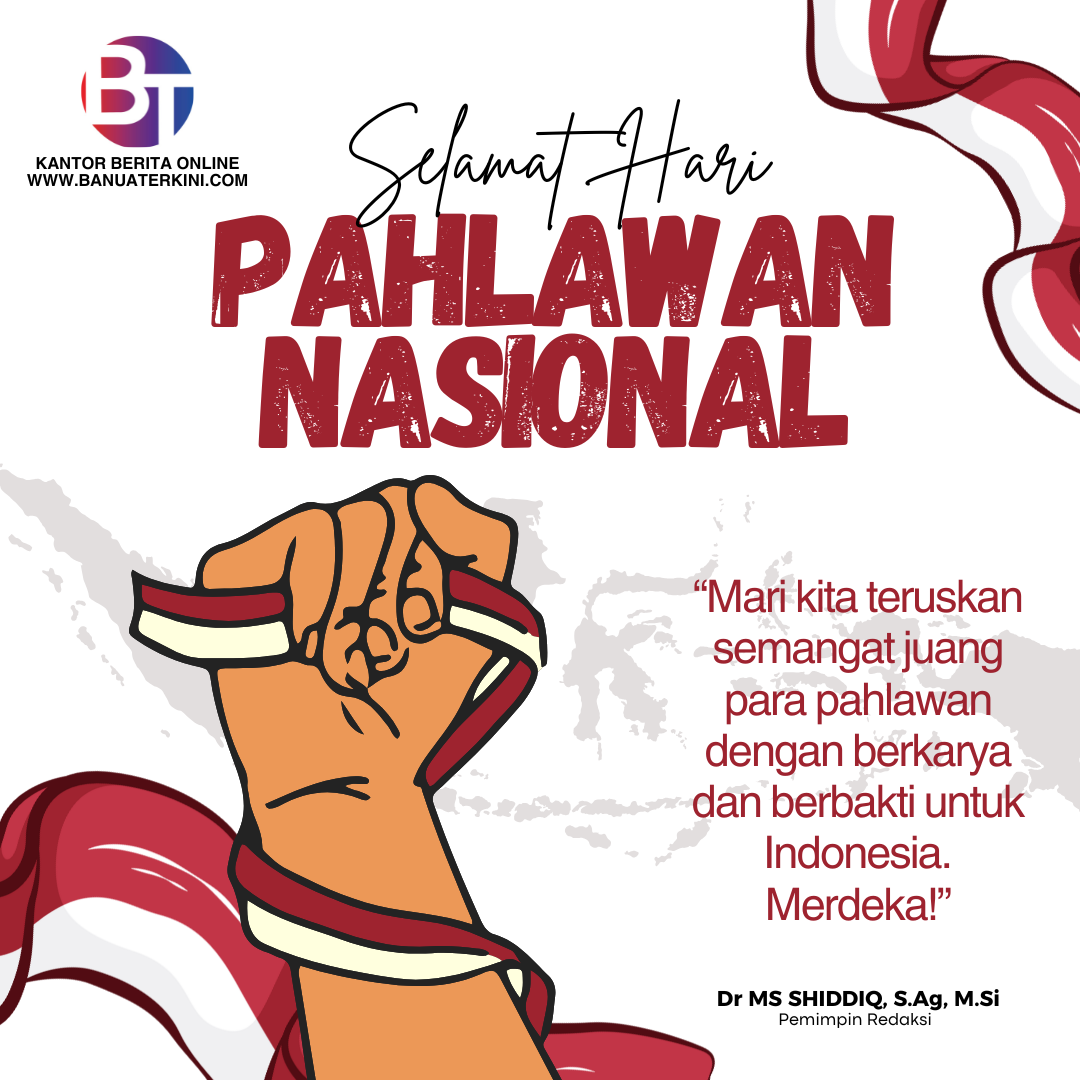
Terpopuler



Terpopuler