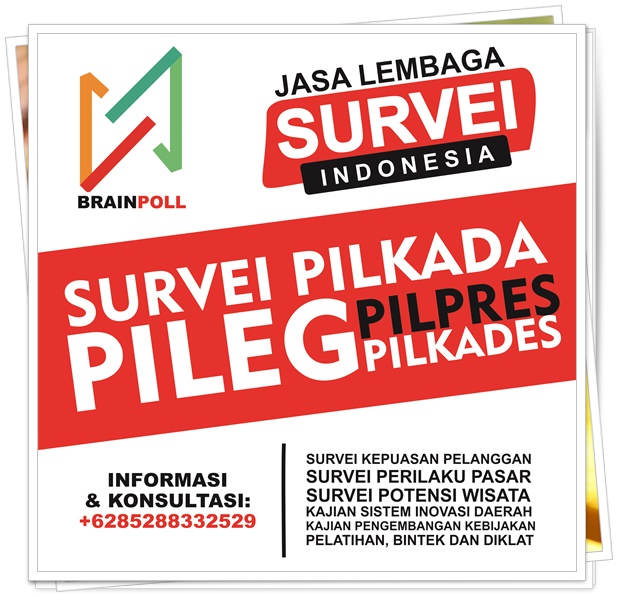Kontroversi Trans7 dan Luka di Wajah Pesantren
Redaksi - Jumat, 17 Oktober 2025 | 16:01 WIB
Post View : 41
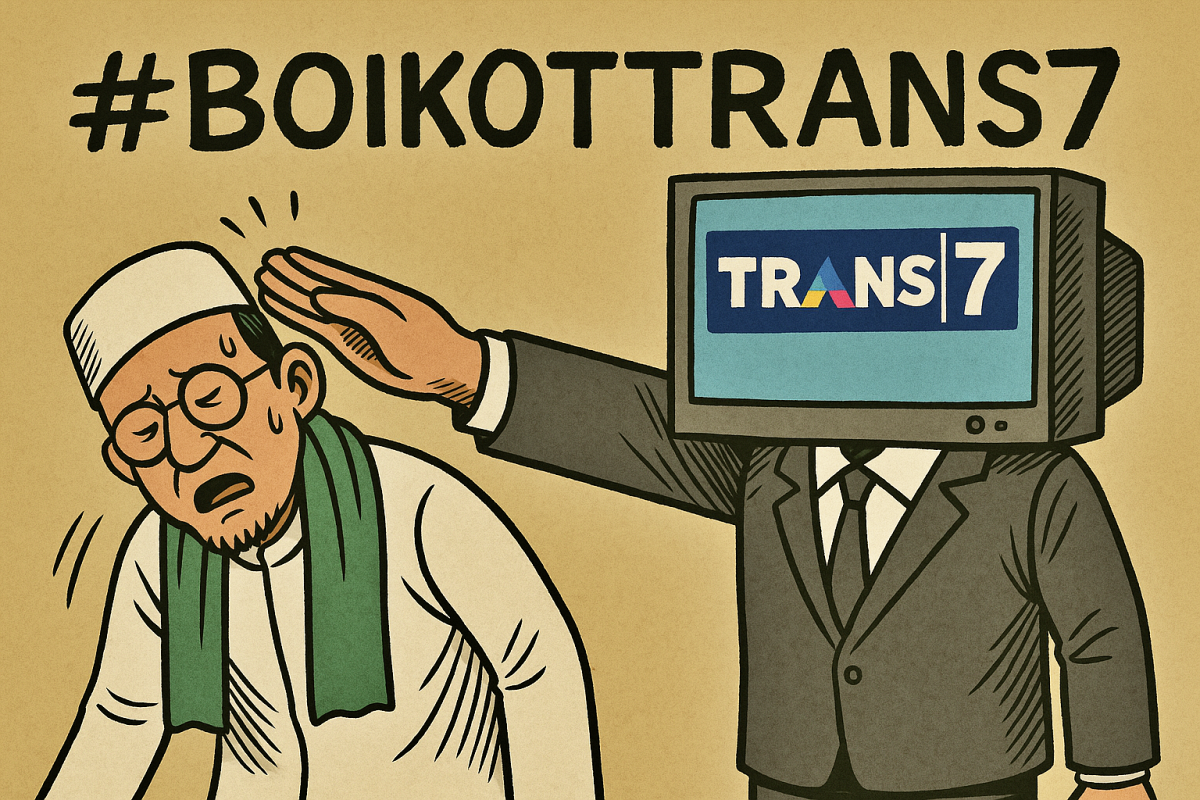
Kontroversi tayangan Expose Uncensored Trans7 yang menampilkan kehidupan santri dan pesantren Lirboyo memicu gelombang reaksi luas di ruang publik. Kritik datang dari berbagai kalangan, mulai dari PBNU hingga alumni pesantren, menyoroti batas etika dan tanggung jawab media dalam membingkai isu keagamaan. Artikel ini mengupas secara mendalam bagaimana kebebasan pers seharusnya dijalankan dengan tetap menghormati simbol keagamaan. Artikel ini menjadi refleksi penting tentang keseimbangan antara hak berekspresi media dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral serta budaya pesantren.
 Oleh: MS Shiddiq *)
Oleh: MS Shiddiq *)
Tayangan televisi bukan sekadar hiburan. Ia adalah cermin budaya dan ruang wacana publik. Saat suatu stasiun televisi melangkah terlalu jauh dalam membingkai narasi sensasional atas pesantren dan kiai, yang terjadi bukan sekadar kontroversi media, melainkan keguncangan moral dan institusional.
Kasus Expose Uncensored Trans7 yang menyinggung kehidupan santri dan wibawa pesantren Lirboyo adalah bahan refleksi penting: sejauh mana media boleh membongkar sisi kelam lembaga keagamaan, dan di mana batas penghormatan hak asasi simbolik?
Apa yang Terjadi di Balik Kamera?
Dalam episode yang ditayangkan 13 Oktober 2025, Expose Uncensored menyajikan narasi provokatif seperti “santrinya minum susu aja kudu jongkok” untuk menggambarkan kehidupan di pondok pesantren.
Tampak pula cuplikan santri merunduk atau “ngesot” demi bersalaman dan menyerahkan amplop kepada kiai. Narasi tersebut dikemas secara dramatis, dengan gaya editing yang menonjolkan gestur dilematis dan visual yang retoris. Sayangnya, Trans7 menyodorkan narasumber internal pesantren sangat terbatas, sedangkan suara penonton lebih banyak muncul sebagai komentar luar.
Dari perspektif komunikasi, pola itu masuk dalam bentuk framing dan agenda setting: media memilih sudut pandang tertentu, mengundang persepsi negatif, lalu menetapkan mana yang menjadi isu utama publik. Tanpa keseimbangan (counter-narrative), penonton dipandu untuk memandang bahwa “kehidupan pesantren = ketertinggalan, relasi kiai-santri = feodalisme.”
Apalagi di ruang digital, tayangan cepat viral, sehingga memicu munculnya tagar #BoikotTrans7 di media sosial. Dalam hitungan jam, publik. khususnya santri dan alumni, bereaksi keras, melakukan republishing cuplikan, menggalang desakan permintaan maaf. Imbasnya, stasiun menghadapi tekanan moral dan institusional sekaligus.
Kritik Terhadap Kebijakan Trans7 dan Etika Redaksi
Respons Trans7 datang belakangan: surat permintaan maaf tertanggal 14 Oktober 2025 yang ditandatangani Direktur Produksi dan Kepala Departemen Programing menyebut adanya “keteledoran kurang teliti” dalam menyajikan konten tersebut. Mereka menegaskan akan melakukan evaluasi agar tak mengulang kesalahan.
Permintaan maaf yang disampaikan Trans7 memang langkah awal yang patut diapresiasi. Namun publik menilai, permintaan maaf semata belum cukup menutup luka simbolik yang telah muncul di kalangan pesantren dan masyarakat luas. PBNU dan sejumlah tokoh keagamaan menuntut langkah lanjutan yang lebih konkret dan transparan.
Yang diharapkan bukan sekadar pernyataan sesal, melainkan upaya sistematis yang menunjukkan tanggung jawab moral dan profesional. Trans7 perlu membuka audit internal secara terbuka, agar publik mengetahui sejauh mana proses penyuntingan dan pengawasan redaksional dijalankan. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan terhadap kredibilitas redaksi.
Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap pedoman produksi konten keagamaan menjadi keharusan. Dunia penyiaran tidak boleh memperlakukan isu agama sebagai sekadar bahan sensasi atau hiburan. Penguatan pedoman etik akan menjadi pagar moral yang mencegah kesalahan serupa di masa depan.
Sebagai bentuk itikad baik, stasiun televisi juga dapat menempuh jalur edukatif, misalnya dengan menayangkan program khusus yang mengangkat kehidupan pesantren secara utuh—bukan karikatural, tetapi reflektif dan mendidik. Tayangan seperti itu bukan hanya menebus kesalahan, tetapi juga memperkaya publik dengan wawasan tentang peran pesantren dalam sejarah bangsa.
Dan yang tak kalah penting, redaksi Trans7 perlu menetapkan batas-batas yang tegas ketika menyajikan kehidupan lembaga agama. Bukan untuk membatasi kebebasan pers, melainkan untuk menjaga agar kebebasan itu tetap beradab dan berpihak pada nilai kemanusiaan.
Dalam kasus ini, Trans7 tampak belum mengumumkan jadwal audit terbuka atau mengundang pihak pesantren sebagai mitra diskusi. Jika kebijakan redaksional hanya “menyesal tapi diam,” potensi kesalahan berulang tetap tinggi.
KPI pun angkat suara: mereka akan menggelar sidang pleno untuk menilai kepatuhan Trans7 terhadap P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). KPI menyebut tayangan itu “mencederai nilai luhur penyiaran” dan mengganggu ruh kebatinan pesantren.
Suara Alumni, dan Kekhawatiran Tokoh NU
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mengeluarkan protes keras atas tayangan tersebut. Menurutnya, konten itu menghina pesantren dan tokoh NU, menyalahi etika jurnalistik dan berpotensi mencabut kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan. Dia memerintahkan Lembaga Bantuan Hukum PBNU untuk menempuh jalur hukum terhadap Trans7 dan Trans Corporation.
Alumni Lirboyo, melalui sejumlah pernyataan resmi, mengecam kuat narasi yang menggambarkan kiai sebagai sosok bergelimang amplop atau berjalan “ngesot.” Mereka menuntut stasiun menarik tayangan tersebut, menerbitkan klarifikasi publik, dan menyebar konten positif tentang pesantren.
Di sisi lain, ada tokoh muda NU yang menyampaikan kritik terhadap respons PBNU: menurut mereka, terlalu keras membela hanya “komunitas NU” bisa dipersepsikan eksklusif dan kontraproduktif dalam ruang publik yang lebih luas.
Implikasi Narasi dan Identitas
Dari kajian komunikasi, sikap Trans7 dan tanggapan publik memperlihatkan bahwa narasi media yang kuat bisa membentuk identitas kolektif, dalam hal ini, pesantren sebagai kelompok yang dieksotifikasi dan dicap “tradisional, kolot, didikte.”
Di sisi lain, komunitas pesantren merespons melalui counter-narrative: merangkul santri, alumni, NU, agar identitas mereka direbut kembali lewat suara bersama.
Di ranah komunikasi organisasi, Trans7 punya peluang memperkuat legitimacy melalui langkah korektif terbuka: dialog publik, pengakuan kesalahan, dan kolaborasi dengan pihak santri atau pesantren untuk menghasilkan konten yang menghormati simbol keagamaan.
Ruang publik Indonesia butuh media yang mampu menjaga proporsi antara kebebasan pers dan penghormatan simbol agama. Bila media mengabaikan sensitivitas simbolik tanpa mekanisme kontrol yang matang, ia bisa memicu konflik sosial yang tak perlu.
Ujian Media dalam Menegakkan Etika
Kasus Trans7 dan Lirboyo bukan sekadar polemik TV, ia adalah ujian moral bagi media dan masyarakat. Apakah media cukup peka untuk menghormati institusi keagamaan meski ingin “membongkar fakta”? Apakah pesantren cukup agresif untuk mempertahankan wibawa simbolik mereka dalam ruang publik massal?
Trans7 mesti membuktikan bahwa permintaan maaf bukan sekadar basa-basi redaksional. Ia harus membuka diri terhadap audit independen, menerima keterlibatan pesantren, dan menunjukkan komitmen nyata. Publik dan lembaga agama punya hak menuntut transparansi serta tanggung jawab simbolik.
Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan, bahwa media besar tidak boleh hanya menjadi panggung sensasi; ia harus menjadi jembatan dialog. Bila gagal, maka televisi bukan hanya mengecewakan satu komunitas, ia merusak kepercayaan publik terhadap institusi media itu sendiri.
*) MS Shiddiq, Pemimpin Redaksi Banuaterkini.com, pemerhati komunikasi publik.
Tags
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Terkini
Kopdes Merah Putih Jadi Harapan Baru Warga Sekadau
Minggu, 19 Oktober 2025 | 10:08 WIB
Whoosh Buka Akses Baru Bandung–Jakarta, Warga Padalarang Rasakan Manfaatnya
Minggu, 19 Oktober 2025 | 09:57 WIB
Tutor SKB Banjarmasin Belajar Coding dan AI untuk Kelas Kesetaraan
Sabtu, 18 Oktober 2025 | 16:46 WIB
BPKPAD: Semua Pajak Daerah di Banjarmasin Sudah Sesuai Aturan Pusat
Jumat, 17 Oktober 2025 | 18:30 WIB
Syamsudin Noor Pastikan Kesiapan Rute Internasional Banjarmasin–Kuala Lumpur
Jumat, 17 Oktober 2025 | 18:05 WIB
BGN Soroti Dapur MBG Tak Layak, Prabowo Turun Hitung Menu
Jumat, 17 Oktober 2025 | 17:27 WIB
Kopdes Merah Putih Jadi Harapan Baru Warga Sekadau
Minggu, 19 Oktober 2025 | 10:08 WIB
Whoosh Buka Akses Baru Bandung–Jakarta, Warga Padalarang Rasakan Manfaatnya
Minggu, 19 Oktober 2025 | 09:57 WIB
Tutor SKB Banjarmasin Belajar Coding dan AI untuk Kelas Kesetaraan
Sabtu, 18 Oktober 2025 | 16:46 WIB
BPKPAD: Semua Pajak Daerah di Banjarmasin Sudah Sesuai Aturan Pusat
Jumat, 17 Oktober 2025 | 18:30 WIB
Syamsudin Noor Pastikan Kesiapan Rute Internasional Banjarmasin–Kuala Lumpur
Jumat, 17 Oktober 2025 | 18:05 WIB
BGN Soroti Dapur MBG Tak Layak, Prabowo Turun Hitung Menu
Jumat, 17 Oktober 2025 | 17:27 WIB



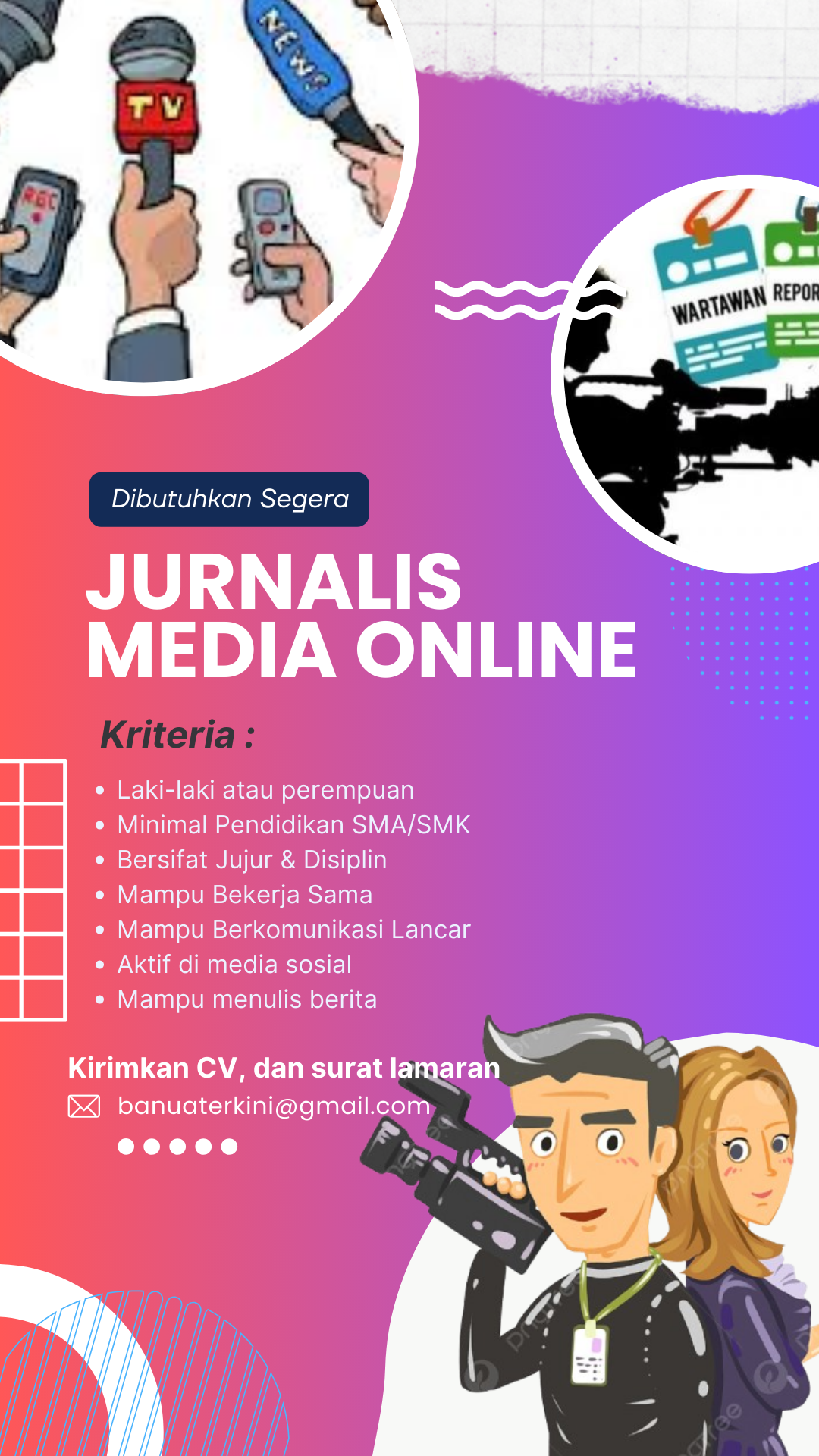
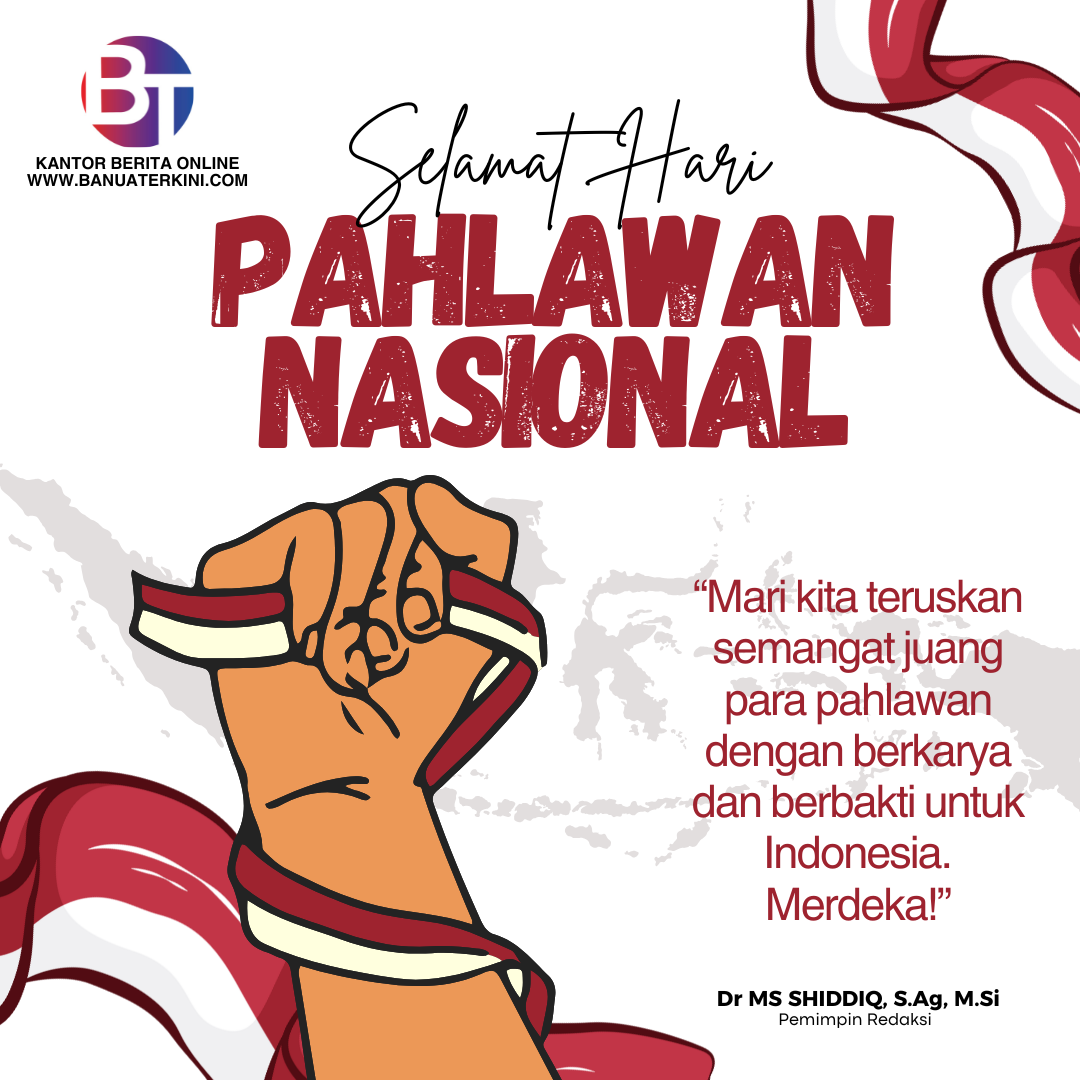
Terpopuler
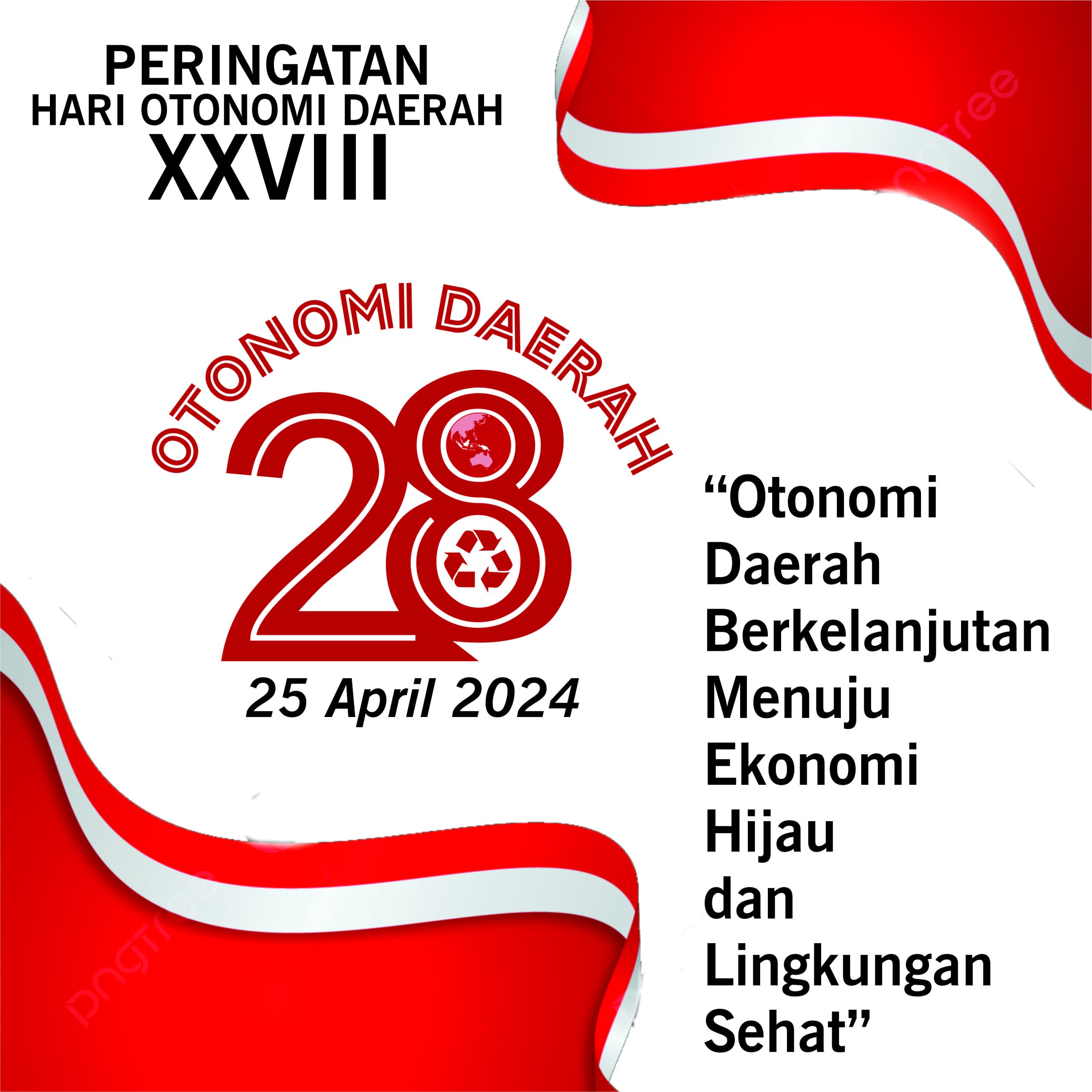


Terpopuler