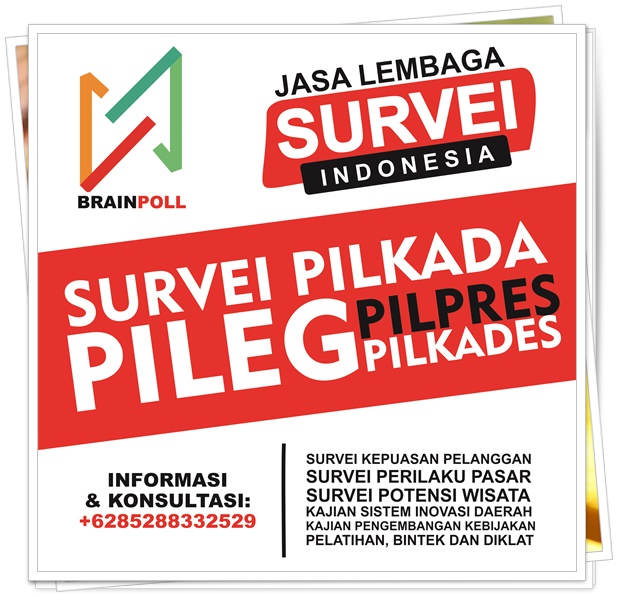Perjuangan Mentor Iklim Indonesia di Climate Reality 2025
Redaksi - Minggu, 6 April 2025 | 20:29 WIB
Post View : 8

Perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, tetapi krisis kemanusiaan yang mengetuk hati dan menuntut aksi nyata. Di tengah kompleksitas tantangan global itu, seorang perempuan Indonesia berdiri sebagai salah satu mentor dalam pelatihan kepemimpinan iklim global Climate Reality Leadership Corps Training 2025.
Banuaterkini.com, JAKARTA - Swary Utami Dewi, aktivis sekaligus pegiat isu keberlanjutan, kepada Banuaterkini.com, Minggu (06/04/2025) mencatatkan kisahnya—tentang komitmen yang terus menyala sejak 2009, harapan yang tak lekang, dan perjuangan yang terus ia jalani demi menjaga mimpi bersama, bumi yang lestari dan adil bagi semua.
Dari Melbourne ke Jakarta, Jejak Seorang Pejuang Iklim
Perjalanan Swary dimulai di Melbourne, Australia, pada tahun 2009.
Di sanalah ia pertama kali mendapat pelatihan langsung dari Al Gore—mantan Wakil Presiden Amerika Serikat dan penerima Nobel Perdamaian—dalam Climate Reality Leadership Corps.
Ia menjadi bagian dari “The First 50” warga Indonesia yang terpilih saat itu.
Bukan sekadar pelatihan, itu menjadi titik balik kesadarannya bahwa perubahan iklim adalah panggilan hidup.
 Dua pelatihan lanjutan menyusul—di Nashville (2010) dan Jakarta (2011)—keduanya juga dipandu langsung oleh Al Gore.
Dua pelatihan lanjutan menyusul—di Nashville (2010) dan Jakarta (2011)—keduanya juga dipandu langsung oleh Al Gore.
Sejak itu, ia menyaksikan gerakan ini tumbuh subur, dari puluhan menjadi ribuan Climate Leaders dari seluruh penjuru Indonesia.
Jejaknya bukan hanya tentang angka, tetapi tentang semangat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Mentor di Masa Pandemi, Deg-degan tapi Berdaya
Pandemi COVID-19 mengubah wajah pelatihan iklim global.
Tak ada lagi ruang konferensi, hanya layar-layar yang mempertemukan para peserta lintas negara.
Swary kala itu dipercaya menjadi mentor dalam pelatihan daring berskala internasional.
Tantangannya bukan hanya materi, tetapi juga adaptasi terhadap platform digital, kendala bahasa, dan dinamika antarbudaya.
Ia mengakui, perasaan senang bercampur cemas mewarnai pengalamannya.
Namun, justru dari keterbatasan itu lahirlah inovasi, kesabaran, dan pembelajaran baru.
“Kami bukan hanya membagikan materi, tapi juga menciptakan ruang aman untuk saling mendengar dan memahami,” kenangnya.
Ditolak Jadi Peserta, Kini Kembali Jadi Mentor
Tahun 2025, Swary kembali mengajukan diri sebagai peserta pelatihan di Indonesia—mungkin dengan harapan bisa sejenak menjadi pembelajar biasa.
Namun takdir berkata lain: ia ditolak sebagai peserta. Tak lama kemudian, ia malah diminta kembali menjadi mentor.
“Padahal kalau jadi peserta bisa duduk manis,” ujarnya sembari tertawa.

Meski terkesan sepele, momen ini justru menunjukkan satu hal: perannya sudah tumbuh melampaui posisi awal.
Ia tak lagi hanya belajar dari pelatihan, tapi menjadi bagian dari mereka yang membentuk arah dan makna pelatihan itu sendiri.
Bahasa Inggris di Meja Enam, Pertemuan Lintas Generasi dan Bangsa
Sebagai mentor, Swary mendampingi kelompok meja 6 yang terdiri dari peserta muda berusia 22–27 tahun.
Salah satunya adalah mahasiswa asing yang sedang studi di Indonesia. Alhasil, seluruh diskusi kelompok menggunakan bahasa Inggris.
Bagi Swary, ini bukan sekadar urusan bahasa, melainkan simbol dari jangkauan isu iklim yang lintas batas negara dan generasi.
“Isu perubahan iklim itu tak mengenal paspor. Ia menyentuh setiap kehidupan, dari Jakarta hingga Kampala,” ungkapnya.
Dan di tengah ruang diskusi yang hangat itu, ia kembali merasakan harapan, bahwa anak-anak muda kini tak lagi menunggu giliran, mereka memilih untuk segera terlibat.
Indonesia Raya Tiga Stanza, Air Mata di Ujung Nada
Pelatihan dibuka dengan prosesi yang jarang dilakukan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lengkap tiga stanza.
Momen itu menggugah emosi banyak peserta, termasuk Swary.
“Saya merinding dan hampir menangis,” katanya.
Lagu itu bukan hanya simbol nasionalisme, tapi pengingat kuat bahwa membela bangsa kini berarti juga membela keberlangsungan hidup rakyatnya dari ancaman iklim.
Kesadaran ini, bagi Swary, telah menjadi fondasi bahwa perjuangan iklim bukan isu luar negeri, bukan pula urusan teknis semata.
Ini adalah bentuk nyata cinta pada tanah air.
Sungai Kesadaran dan Batu Cadas Penolakan
Namun perjuangan ini tak pernah mudah.
Swary menyebut banyak pihak yang masih menyangkal realitas perubahan iklim—terutama mereka yang diuntungkan dari eksploitasi sumber daya alam.
“Kalau perjuangan ini ibarat aliran sungai, maka batu cadas besar adalah kepentingan ekonomi dan politik yang terus menghalangi,” ujarnya.
Meski begitu, ia percaya, seperti sungai yang selalu menemukan celah di antara batu-batu, gerakan perubahan akan terus mengalir.
Ia tak akan berhenti hanya karena dihadang. Justru di situlah letak kekuatan: ketekunan untuk terus mencari celah, mengalir, dan menyuburkan kesadaran.
Lintas Isu, Lintas Jalan Hidup
Pelatihan tahun ini juga mempertemukannya kembali dengan para sahabat lama dari beragam isu yaitu dari lintas agama dan spiritualitas, hingga demokrasi dan hak asasi manusia.

Pertemuan lintas jalan hidup ini semakin menegaskan bahwa krisis iklim bukan urusan satu sektor atau komunitas saja. Ia menyentuh semua sisi kehidupan.
“Kalau kamu tidak kena banjir langsung, kamu bisa terjebak macet karena banjir itu. Kalau tidak kena panas ekstrem, kamu bisa merasakan dampaknya melalui udara tak sehat,” ucapnya.
Semua saling terkait, dan karenanya, perjuangan ini adalah perjuangan kolektif.
Mimpi yang Tak Lagi Sekadar Harapan
Melihat antusiasme peserta muda, kecanggihan panitia tanpa event organizer, dan semangat mentor-mentor lainnya, Swary merasa harapan itu kini tumbuh nyata.
“Mimpi untuk bumi yang lebih baik bukan sekadar hopium,” ujarnya.
“Itu bukan khayalan. Itu nyata—dan makin nyata karena didukung dan digerakkan banyak orang.”
Baginya, menjadi mentor bukan lagi sekadar berbagi ilmu, tapi tentang merawat api kecil yang bisa menyalakan lilin-lilin perubahan di berbagai penjuru negeri.
“Dan aku selalu bahagia menjadi bagian dari gerakan itu,” tutupnya, penuh rasa syukur dan keyakinan.
Tags
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Terkini
UNUKASE Dukung Polri Humanis dan Responsif di HUT Bhayangkara ke-79
Rabu, 2 Juli 2025 | 18:28 WIB
Putusan MK Pisahkan Pemilu, Pemerintah Tunggu Arahan Prabowo
Selasa, 1 Juli 2025 | 22:24 WIB
Di Marabahan, IPABI Kalsel Gaungkan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Hebat
Selasa, 1 Juli 2025 | 10:21 WIB
Bangun Industri Baterai, Prabowo Ungkap Misi Hijau Indonesia
Senin, 30 Juni 2025 | 10:40 WIB
Zainudin Resmi Jabat Komandan Menwa UNUKASE, Ajak Mahasiswa Aktif Berorganisasi
Minggu, 29 Juni 2025 | 20:32 WIB
Aksi Bela Palestina di Tugu Kujang Soroti Lemahnya Keberpihakan Negara
Sabtu, 28 Juni 2025 | 12:05 WIB
UNUKASE Dukung Polri Humanis dan Responsif di HUT Bhayangkara ke-79
Rabu, 2 Juli 2025 | 18:28 WIB
Putusan MK Pisahkan Pemilu, Pemerintah Tunggu Arahan Prabowo
Selasa, 1 Juli 2025 | 22:24 WIB
Di Marabahan, IPABI Kalsel Gaungkan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Hebat
Selasa, 1 Juli 2025 | 10:21 WIB
Bangun Industri Baterai, Prabowo Ungkap Misi Hijau Indonesia
Senin, 30 Juni 2025 | 10:40 WIB
Zainudin Resmi Jabat Komandan Menwa UNUKASE, Ajak Mahasiswa Aktif Berorganisasi
Minggu, 29 Juni 2025 | 20:32 WIB
Aksi Bela Palestina di Tugu Kujang Soroti Lemahnya Keberpihakan Negara
Sabtu, 28 Juni 2025 | 12:05 WIB


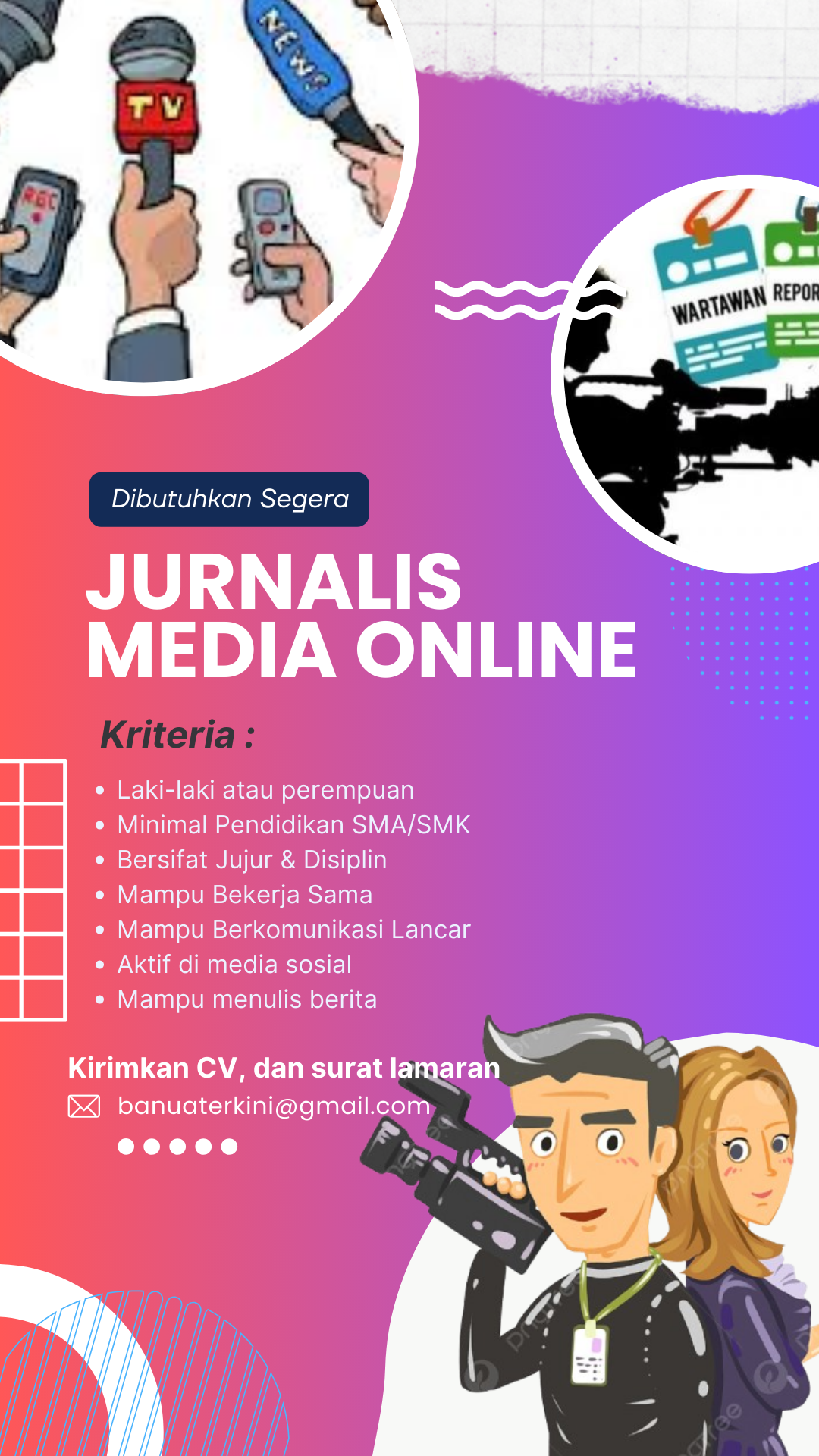
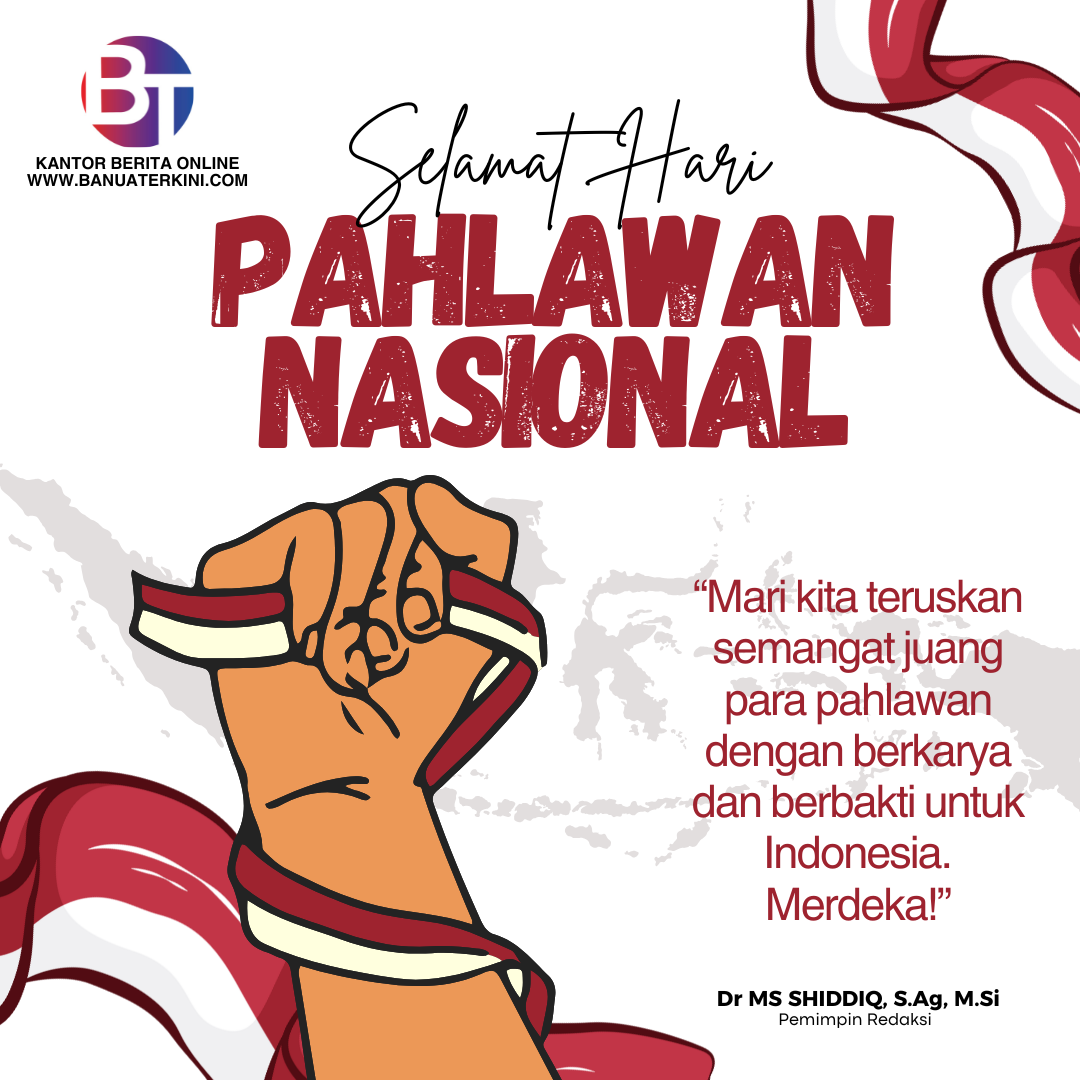
Terpopuler



Terpopuler