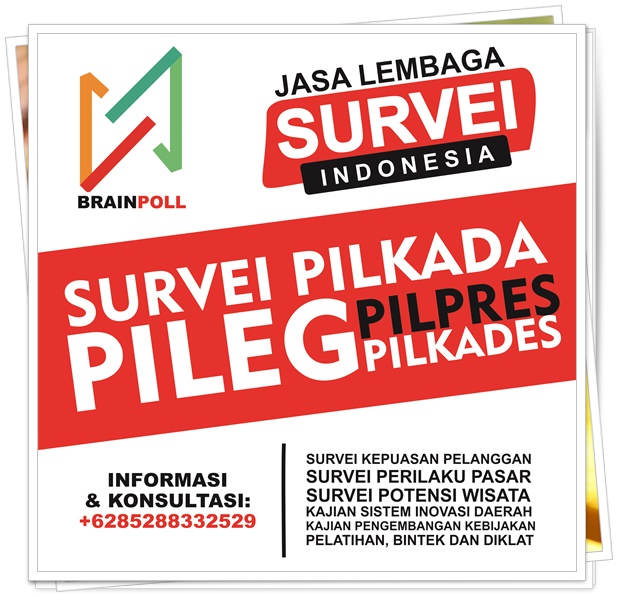Ibu Bumi, Ibu Kehidupan
Redaksi - Sabtu, 24 Desember 2022 | 12:44 WIB
Post View : 38

Redaksi:
Tulisan ini sudah pernah dimuat di laman hijauku.com dengan judul yang sama. Atas seijin penulisnya, redaksi menurunkan kembali tulisan ini, mengingat substansi yang ditulisnya tidak semata menyangkut persoalan kemanusiaan antara anak dengan seorang ibunya, tetapi lebih dari itu Swary Utami Dewi hendak menggugah kepedulian kita pada 'ibu dunia', ibu bumi, lingkungan dan alam sekitarnya, yang sebagian besar rusak karena ulah tangan-tangan manusia.
Dalam perayaan Hari Ibu kali ini saya ingin menghubungkan Hari Ibu dengan cinta dan penghargaan terhadap Ibu Bumi.
Oleh: Swary Utami Dewi
 Hari ini 22 Desember. Sudah hampir pasti di Indonesia bertebaran ucapan mengungkapkan kasih sayang terhadap ibu. Ibu yang melahirkan dan membesarkan. Kasih ibu sepanjang masa. Ada juga yang sibuk bergiat dengan beberapa kegiatan perayaan khas “hari ibu”. Dominan yang muncul adalah lomba masak, berkebaya atau hal-hal yang mengembalikan perempuan dalam konteks domestik (domestifikasi): “masak, macak, manak”. Lebih mirip seperti “Mother’s Day” di luar sana.
Hari ini 22 Desember. Sudah hampir pasti di Indonesia bertebaran ucapan mengungkapkan kasih sayang terhadap ibu. Ibu yang melahirkan dan membesarkan. Kasih ibu sepanjang masa. Ada juga yang sibuk bergiat dengan beberapa kegiatan perayaan khas “hari ibu”. Dominan yang muncul adalah lomba masak, berkebaya atau hal-hal yang mengembalikan perempuan dalam konteks domestik (domestifikasi): “masak, macak, manak”. Lebih mirip seperti “Mother’s Day” di luar sana.
Di lain sisi, akan ada pihak yang paham tentang sejarah lahirnya Hari Ibu, yang memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi lama sebelum Indonesia merdeka; Bahwa perayaan Hari Ibu sangat lekat dengan gerakan perjuangan kaum perempuan dalam merebut kemerdekaan dan memperjuangkan hak perempuan. Bahwa sejarah Hari Ibu berbeda dengan apa yang banyak diketahui selama ini.
Hari Ibu merujuk pada sejarah diadakannya Kongres Perempuan Indonesia pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh 30-an organisasi perempuan Jawa dan Sumatra. Perempuan harus bersatu untuk memajukan nasib perempuan dan perempuan menjadi komponen penting dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi semangat Hari Ibu 22 Desember berbeda dengan Mother’s Day yang dirayakan setiap 10 Mei.
Tanpa bermaksud menambah kritik terhadap praktik cinta kasih kepada setiap ibu (yang bagi saya merupakan pejuang kehidupan sepanjang masa), dalam perayaan Hari Ibu kali ini saya ingin menghubungkan Hari Ibu dengan cinta dan penghargaan terhadap Ibu Bumi. Ibu Bumi tentu saja adalah satu-satunya bumi di mana setiap kehidupan dimungkinkan dan ada; Di mana kehidupan bisa berlanjut dan berkelanjutan.
Memori saya kembali suatu ketika saat saya berada di Kabupaten Jayapura, Papua, tahun 2016. Saat itu saya banyak berbincang dengan para mama, bapak dan orang adat di sana dan belajar konsep Tana Papua sebagai “ibu” yang menyusui dan menjaga manusia dan segala yang ada di dalamnya. Maka jika Tana Papua dirusak, maka sama artinya dengan mengacak-acak tubuh ibu yang kita cintai.
Ibu Bumi inilah yang sekarang sedang dalam posisi sekarat dan tidak berdaya. Karena aktivitas anak-anaknya, para manusia,, yang seringkali begitu gegabah bahkan begitu serakah, mengeksploitasi tubuh Ibu Bumi, mengeluarkan dan menggunakan berbagai sumber daya alam (misalnya minyak dan batu bara) yang pada gilirannya hasil penggunaan sumber daya tersebut menghasilkan gas rumah kaca (misalnya karbon). Gas rumah kaca inilah yang makin mencekik nafas kehidupan Ibu Bumi.
Lalu, manusia juga menerabas hutan — tanpa berpikir kelanjutannya — laksana mencukur rambut mahkota Ibu Bumi dan mengubahnya menjadi berbagai produk untuk menunjang hidup, bahkan kemudian gaya hidup manusia modern. Manusia yang merupakan anak Sang Ibu ini berulah pula dengan beragam langgam ekonomi politik pada saat harus duduk bersama untuk menentukan apa yang terbaik untuk menolong Ibu Bumi yang sedang sekarat ini. Berbagai perundingan, negosiasi, kesepakatan lahir… Mampukah itu meringankan derita Ibu? Nurani dan masa depankah yang terbayang saat satu keputusan politik diambil? Ataukah hanya pertolongan oksigen sementara untuk Ibu yang sedang terengah-engah menahan ajal?
Dalam pikiran banyak orang, bisa jadi manusia berbuat banyak dalam konteks pemanasan global dan perubahan iklim adalah untuk menolong bumi, menyelamatkan bumi. Padahal fakta filosofis, yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Terbayangkah jika Ibu Bumi sudah tidak sanggup menyangga kehidupan karena ulah tidak bijaksana manusia, maka kehidupan siapa yang sebenarnya dipertaruhkan? Ya kehidupan umat manusia. Terbayangkah jika Ibu Bumi “tiada” maka siapa pula yang tiada? Sudah pasti manusia. Ibu Bumi tiada, tiada pula manusia dan kehidupan lain yang saling menyangga sebagai ekosistem.
Saya kembali tercenung. Ibu Bumi sudah begitu rupa melahirkan, menyusui, membesarkan anak-anaknya, mengapa sang anak bisa begitu durhaka menghancurkan ibu kehidupannya? Jika Ibu Bumi hancur, maka siapakah yang sebenarnya musnah?
Maka, ajang 22 Desember ini, di balik segala macam kritik terhadap pemaknaannya, mengapa tidak kita pergunakan untuk menunjukkan cinta sejati kepada Ibu kehidupan manusia? Jika cinta kepada Ibu adalah cinta tiap hari, bukan hanya pada 22 Desember, maka tunjukkan juga cinta itu kepada Ibu Bumi setiap saat, setiap waktu. Dan setiap dari kita sebagai anak-anak kehidupan pasti bisa melakukannya.
Selamat Hari Ibu, Selamat Hari Perempuan.
Selamat Hari Ibu Bumi, Ibu Kehidupan kita semua.
Tags
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Terkini
Kampus IBITEK Tingkatkan Literasi Pasar Modal dan Kewirausahaan
Rabu, 15 Januari 2025 | 08:00 WIB
Mediator Profesional Dorong Investasi dan Ekonomi Kalsel
Selasa, 14 Januari 2025 | 22:04 WIB
KPK Sita Aset Rp476,9 Miliar dari Skandal Eks Bupati Kukar
Selasa, 14 Januari 2025 | 21:00 WIB
Viral Isu Buzzer, TNI AL Tegaskan Rp 100 Miliar Anggaran Pengamanan Data
Selasa, 14 Januari 2025 | 19:42 WIB
Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada Banjarbaru Digelar 20 Januari 2025
Selasa, 14 Januari 2025 | 10:55 WIB
Bahas Sungai Kemuning dan Program Nasional, PMII Temui Ketua DPRD Banjarbaru
Selasa, 14 Januari 2025 | 09:40 WIB
Tidak Ada Anggaran Tunjangan Dosen ASN, Pemerintah Tengah Cari Solusi
Senin, 13 Januari 2025 | 21:45 WIB
Ini Alasan KPK tak Menahan Hasto Usai Diperiksa
Senin, 13 Januari 2025 | 20:42 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK Terkait
Senin, 13 Januari 2025 | 11:56 WIB
Kampus IBITEK Tingkatkan Literasi Pasar Modal dan Kewirausahaan
Rabu, 15 Januari 2025 | 08:00 WIB
Mediator Profesional Dorong Investasi dan Ekonomi Kalsel
Selasa, 14 Januari 2025 | 22:04 WIB
KPK Sita Aset Rp476,9 Miliar dari Skandal Eks Bupati Kukar
Selasa, 14 Januari 2025 | 21:00 WIB
Viral Isu Buzzer, TNI AL Tegaskan Rp 100 Miliar Anggaran Pengamanan Data
Selasa, 14 Januari 2025 | 19:42 WIB
Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada Banjarbaru Digelar 20 Januari 2025
Selasa, 14 Januari 2025 | 10:55 WIB
Bahas Sungai Kemuning dan Program Nasional, PMII Temui Ketua DPRD Banjarbaru
Selasa, 14 Januari 2025 | 09:40 WIB
Tidak Ada Anggaran Tunjangan Dosen ASN, Pemerintah Tengah Cari Solusi
Senin, 13 Januari 2025 | 21:45 WIB
Ini Alasan KPK tak Menahan Hasto Usai Diperiksa
Senin, 13 Januari 2025 | 20:42 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Penuhi Panggilan KPK Terkait
Senin, 13 Januari 2025 | 11:56 WIB
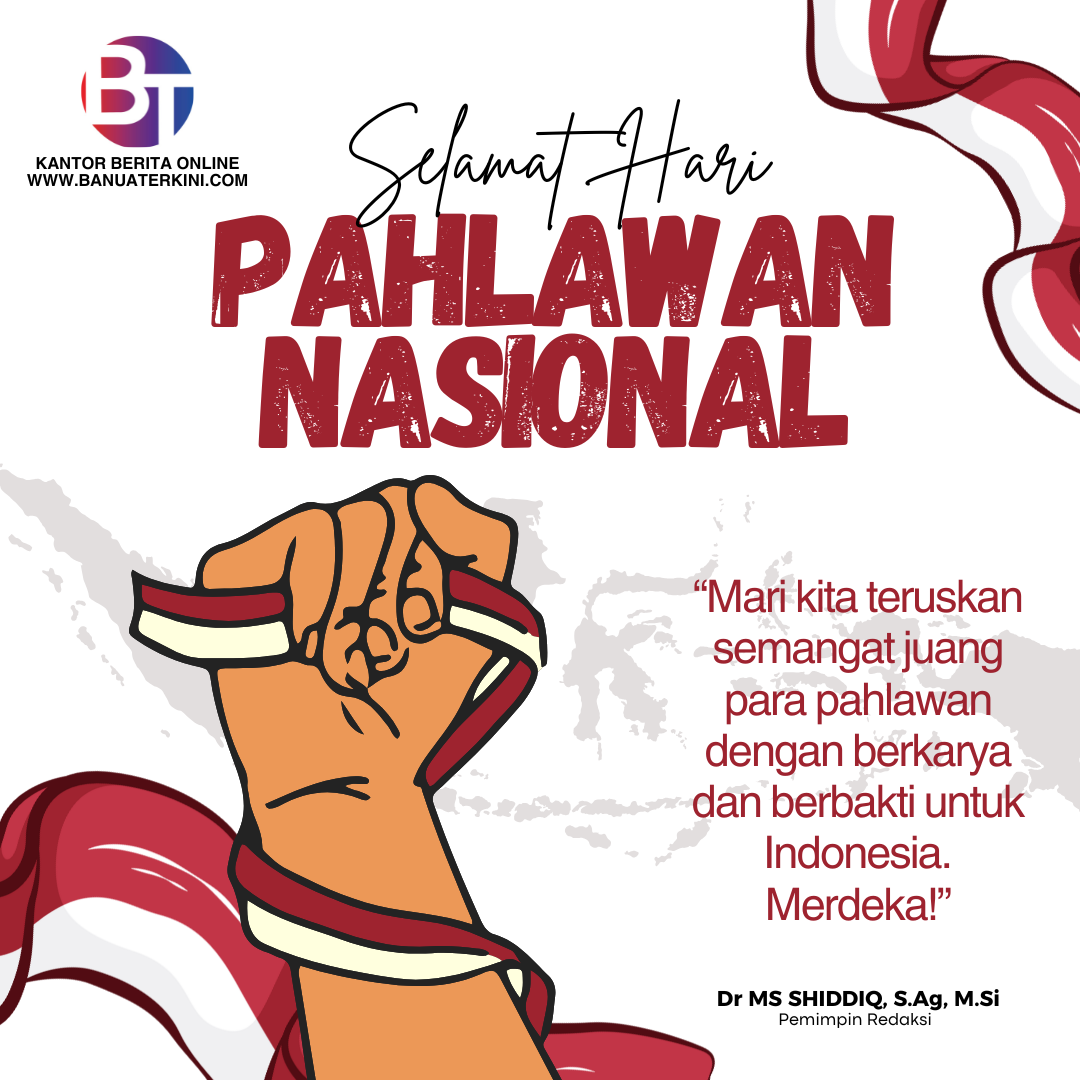

Terpopuler





Terpopuler