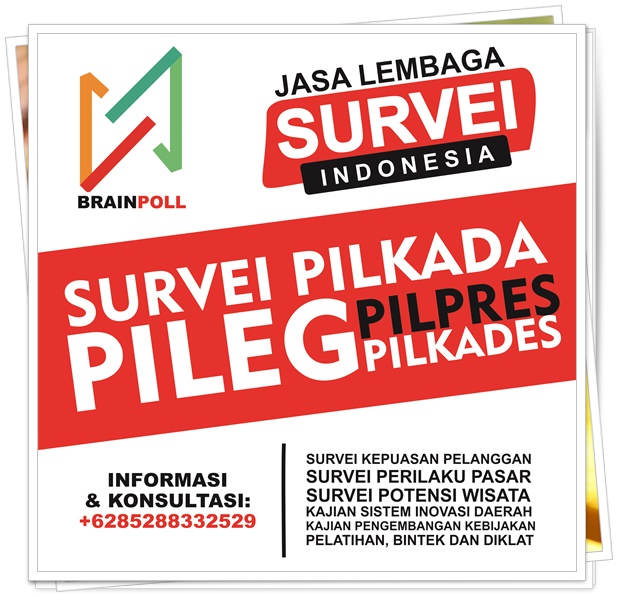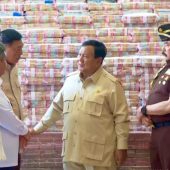Panggung Pilkada Banjarbaru dan Ironi Aturan Main
Redaksi - Jumat, 1 November 2024 | 07:43 WIB
Post View : 489

Politik praktis di Indonesia memang menunjukkan bahwa aturan kerap kali bersifat lentur, bisa dibentuk atau bahkan dipelintir sesuai kebutuhan. Generasi muda yang mengikuti berita ini, terutama mereka yang bercita-cita memperbaiki tata kelola di tingkat lokal, mendapat pelajaran yang pahit. Mereka menyaksikan bahwa proses pencalonan bukan hanya soal siapa yang punya visi terbaik untuk masyarakat, melainkan siapa yang mampu bertahan dalam jebakan intrik dan kepentingan.
 Oleh: MS Shiddiq
Oleh: MS Shiddiq
Peristiwa pembatalan pencalonan pasangan Aditya Mufti Ariffin dan Said Abdullah (Habib Abdullah) sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru 2024 memperlihatkan sebuah kisah getir yang menampilkan wajah asli politik lokal kita. Keputusan ini, yang dibingkai dalam tajuk resmi sebagai "penegakan aturan pemilu," pada akhirnya mengajarkan kita semua, terutama generasi milenial dan Gen Z, tentang "pendidikan politik" yang nyata—meski pahit dan penuh ironi.
Bagi generasi muda yang baru mengenal dunia politik, mungkin inilah kenyataan tentang seleksi kepemimpinan daerah yang sebenarnya: panggung besar di mana aturan bisa berubah menjadi senjata untuk menjegal atau melanggengkan kekuasaan sesuai kebutuhan.
Dari perspektif komunikasi politik, drama ini menghadirkan ironi yang mencolok. Pasangan Aditya-Habib, yang dikenal sebagai kandidat kuat, tiba-tiba tersungkur oleh rekomendasi Bawaslu atas dasar “dugaan pelanggaran pemilu.” Yang menggelitik adalah bahwa rekomendasi ini berawal dari laporan pesaing politik mereka sendiri, yang jelas diuntungkan oleh "pengusiran" ini. Apakah aturan-aturan pemilu ini sungguh diterapkan untuk keadilan, atau lebih kepada menyusun panggung yang hanya menyisakan aktor yang diinginkan?
Politik praktis di Indonesia memang menunjukkan bahwa aturan kerap kali bersifat lentur, bisa dibentuk atau bahkan dipelintir sesuai kebutuhan. Generasi muda yang mengikuti berita ini, terutama mereka yang bercita-cita memperbaiki tata kelola di tingkat lokal, mendapat pelajaran yang pahit. Mereka menyaksikan bahwa proses pencalonan bukan hanya soal siapa yang punya visi terbaik untuk masyarakat, melainkan siapa yang mampu bertahan dalam jebakan intrik dan kepentingan.
Ironi di Balik Aturan
Dalam teori komunikasi politik, tindakan seperti ini disebut sebagai strategi framing—di mana aturan digunakan untuk menciptakan persepsi tertentu. Di mata publik, pembatalan Aditya-Habib seakan-akan menjadi bentuk penegakan aturan.
Namun, dalam praktiknya, ini lebih dari sekadar "mengikuti aturan"; ini adalah tindakan menyusun panggung demi menyingkirkan kompetitor yang kuat. Penggunaan aturan dalam konteks seperti ini mengaburkan batas antara keadilan dan kepentingan, yang pada akhirnya meninggalkan jejak ketidakpercayaan di benak masyarakat.
Bagaimana tidak? Pasangan yang kuat dan berpotensi menjadi favorit publik kini disingkirkan melalui narasi formal yang disusun dengan rapi. Jika generasi milenial dan Gen Z masih memiliki idealisme dalam menilai proses politik, mereka justru dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa aturan bisa berubah menjadi alat untuk menciptakan "drama" sesuai dengan peran yang diinginkan para aktor di balik layar.
Tags
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Terkini
Sektor Digital Dongkrak Pajak Negara Capai Rp42,53 Triliun
Rabu, 22 Oktober 2025 | 16:46 WIB
Pendidikan Rakyat Jadi Fokus Prabowo Bangun Generasi Tangguh
Rabu, 22 Oktober 2025 | 16:13 WIB
Cahaya dari Hutan Meratus, Listrik Mandiri yang Menghidupkan Negeri
Rabu, 22 Oktober 2025 | 13:47 WIB
DPRD Bogor Bahas Raperda Disabilitas dan Pengelolaan Sampah
Rabu, 22 Oktober 2025 | 12:21 WIB
Majelis Hakim Pertimbangkan Kemanusiaan, Kerry Riza Dipindah ke Salemba
Rabu, 22 Oktober 2025 | 12:20 WIB
Tirta Kahuripan Harumkan Nama Bogor di Mandaya Award 2025
Rabu, 22 Oktober 2025 | 12:10 WIB
Rp13 Triliun Uang Korupsi Bisa Bangun 600 Kampung Nelayan
Selasa, 21 Oktober 2025 | 21:11 WIB
Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, KPK Minta Laporan dari Mahfud
Selasa, 21 Oktober 2025 | 19:17 WIB
Bidan Rahmaniah Tewas Dirampok, Pelaku Diduga Tetangga Korban
Selasa, 21 Oktober 2025 | 06:13 WIB
Kejagung Serahkan Rp13 Triliun Sitaan Korupsi CPO ke Negara
Selasa, 21 Oktober 2025 | 04:42 WIB
Sektor Digital Dongkrak Pajak Negara Capai Rp42,53 Triliun
Rabu, 22 Oktober 2025 | 16:46 WIB
Pendidikan Rakyat Jadi Fokus Prabowo Bangun Generasi Tangguh
Rabu, 22 Oktober 2025 | 16:13 WIB
Cahaya dari Hutan Meratus, Listrik Mandiri yang Menghidupkan Negeri
Rabu, 22 Oktober 2025 | 13:47 WIB
DPRD Bogor Bahas Raperda Disabilitas dan Pengelolaan Sampah
Rabu, 22 Oktober 2025 | 12:21 WIB
Majelis Hakim Pertimbangkan Kemanusiaan, Kerry Riza Dipindah ke Salemba
Rabu, 22 Oktober 2025 | 12:20 WIB
Tirta Kahuripan Harumkan Nama Bogor di Mandaya Award 2025
Rabu, 22 Oktober 2025 | 12:10 WIB
Rp13 Triliun Uang Korupsi Bisa Bangun 600 Kampung Nelayan
Selasa, 21 Oktober 2025 | 21:11 WIB
Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, KPK Minta Laporan dari Mahfud
Selasa, 21 Oktober 2025 | 19:17 WIB
Bidan Rahmaniah Tewas Dirampok, Pelaku Diduga Tetangga Korban
Selasa, 21 Oktober 2025 | 06:13 WIB
Kejagung Serahkan Rp13 Triliun Sitaan Korupsi CPO ke Negara
Selasa, 21 Oktober 2025 | 04:42 WIB



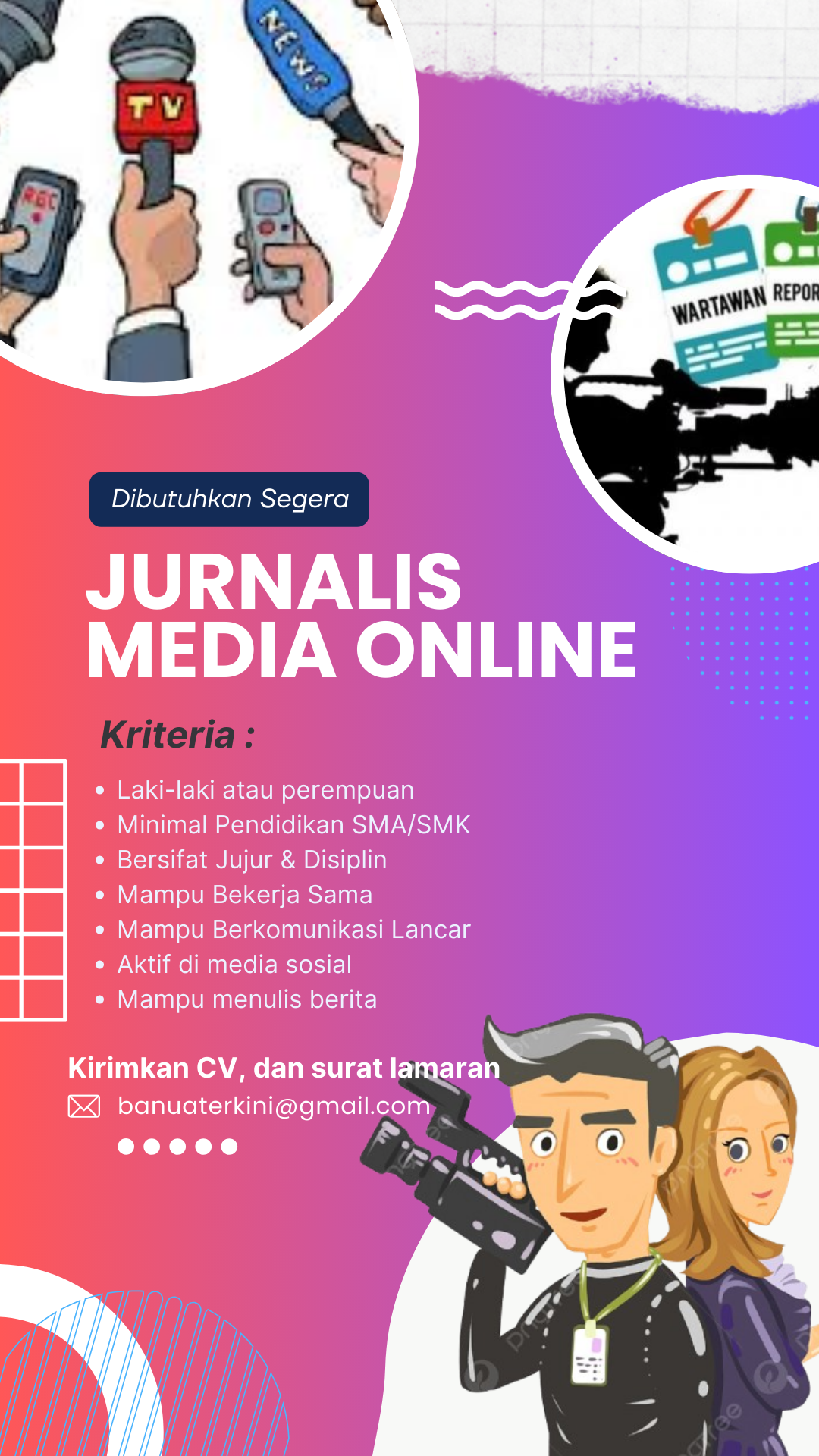
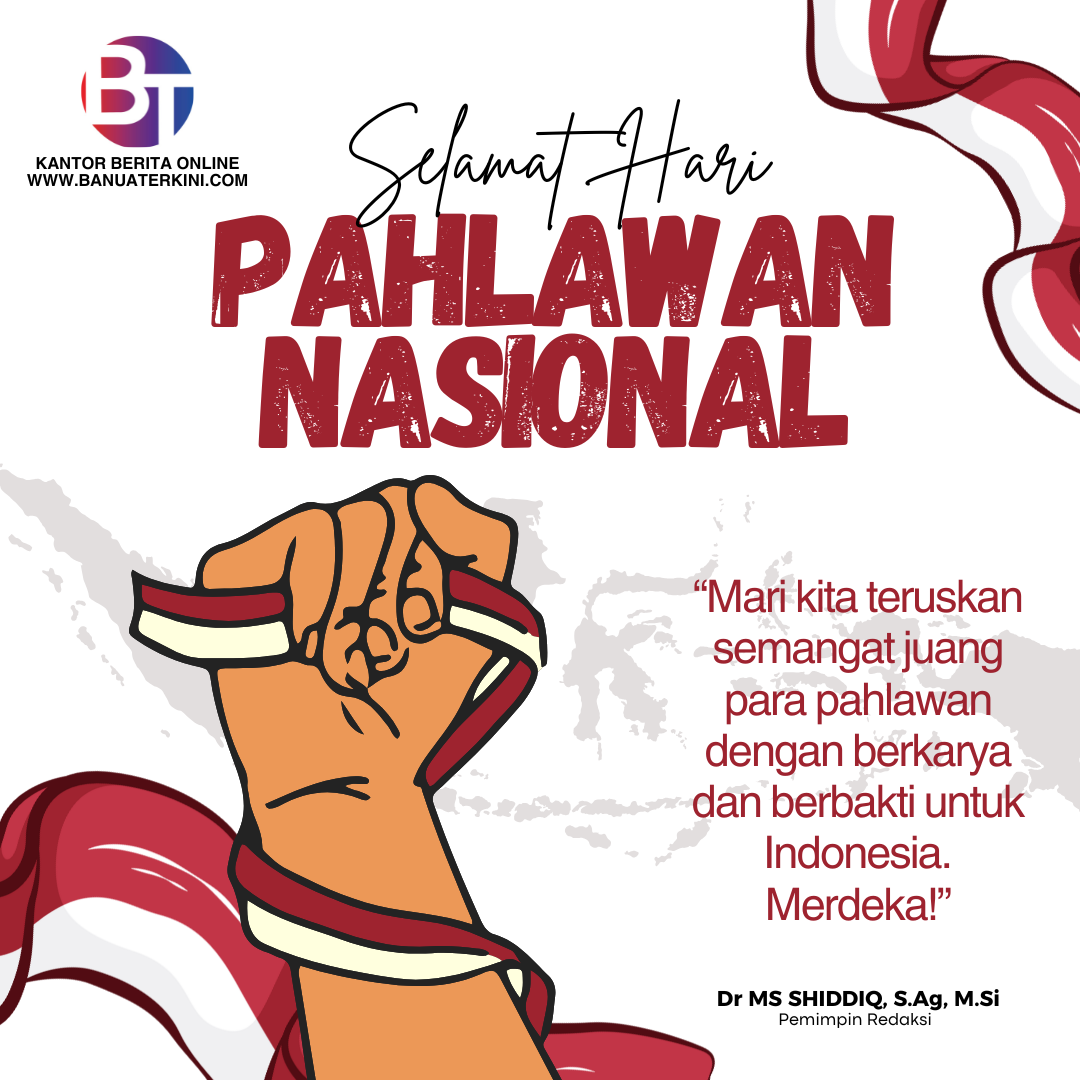
Terpopuler



Terpopuler